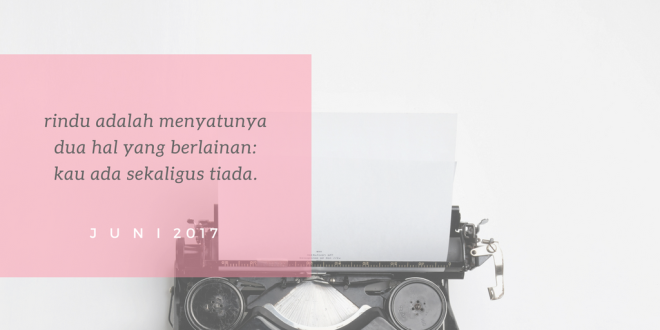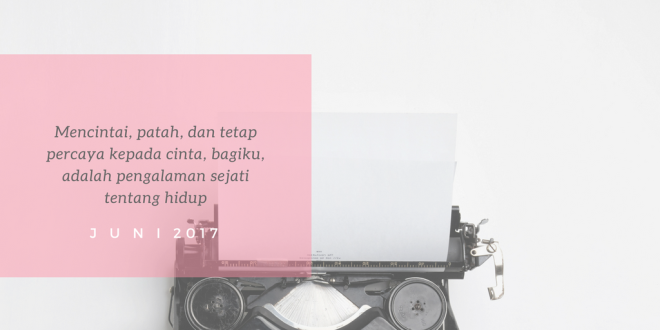
“This is a good sign, having a broken heart. It means we have tried for something.”
— Elizabeth Gilbert (Eat, Pray, Love)
Kehidupan manusia hanya berisi dua hal: ketidakpastian dan ketidakpastian. Kehidupan adalah pertanyaan, tanpa tanda tanya. Seperti Tuhan, kau merasa begitu mengenalnya sekaligus merasa tidak tahu apa-apa tentangnya. Kau dan aku tinggal di dalam kehidupan yang demikian, tak pasti. Dan kita membicarakan hati di dalam ketidakpastian itu.
Ketidakpastian — atau kehidupan itu — akan mematahkan hatimu. Tak perduli seberapa hebat kau jaga hatimu itu. Sekali, dua kali, atau berkali-kali. Entah dalam urusan cinta atau apa saja. Dan, ketika kau berkata, “Aku sedang patah hati!” Pasti bukan liver yang kau maksudkan, melainkan satu titik tersembunyi atau ruang paling dalam dan rahasia di dirimu, yakni sebuah hati yang tak tampak, tetapi seolah-olah merupakan tempat segala rasa dan asa bersemayam, dan menjadi sedemikian nyata di dalam perasaanmu tentang hidup; dirimu, benda-benda, manusia lain, dan peristiwa-peristiwa, bahkan yang telah lama lewat: kenangan.
Hati — Di dalam hampir semua tradisi besar dunia, hati dialami dan dipahami sebagai inti sebuah pribadi, titik pusat di mana segala sesuatu yang dapat disebut sebagai kehidupan manusia tersimpan dan bergejolak. Hati adalah ruang maha semesta. Tak seorang pun, bahkan penyair, dapat mengukur seluas apa hati itu. Namun, hati pun kadang bisa menjadi sempit dan tertutup seperti sebuah kamar kecil dengan pintu dan jendela yang terkunci. Keluasan dan kepengapan hati sesungguhnya terletak pada keyakinan manusia tentang hidup. Sedangkan keyakinan manusia tentang hidup ditentukan oleh bagaimana ia memetik makna dari pengalaman-pengalaman atau peristiwa-peristiwa yang dialaminya.
Patah hati — karena apa pun — cenderung membuat kau surut, menutup pintu hati, dan sembunyi. Seolah-olah seluruh dunia dan semua manusia adalah jahat dan mematikan. Kau merasa tidak ada yang dapat kau percaya. Bahkan pada titik tertentu di dalam patahmu, Tuhan pun kau pertanyakan. Sebenarnya, itu kecenderungan yang manusiawi. Ketika berhadapan atau dikelilingi kegagalan atau kehilangan yang berujung lara. Seolah-olah tidak ada lagi yang bisa kau percaya. Inilah saat-saat di mana semua hal tampak mustahil untuk dimaknai, hampa, dan sia-sia.
Ketidakpastian — Sejak awal sudah kukatakan bahwa kehidupan telah sedemikian adanya. Tidak ada yang dapat manusia pastikan dari kehidupan. Dan jika tidak ada yang pasti, maka harapan adalah yang paling berbahaya sekaligus yang paling mungkin memberi kepada manusia, kepada kau dan aku, sebuah keberanian untuk menghadapi ketidakpastian. Di dalam ketidakpastian kehidupan, harapan bisa menjadi obat sekaligus racun. Barangkali kau pernah berharap dia membalas cintamu, tetapi kenyataannya dia membalas cinta seseorang yang lain. Kau menelan sendiri harapanmu yang tiba-tiba saja terasa bagitu pahit dan panas bagai bisa. Apa lagi yang bisa aku katakan tentang itu? Hidup memang demikian. Patah hati adalah biasa, dalam arti: kadang tak terhindarkan. Namun, apa yang hendak aku persoalkan adalah hatimu, hati kita. Sesudah patah, apakah kau berani berharap sekali lagi?
Aku percaya, terlepas dari semua peristiwa yang dialami, entah itu yang membuat bahagia atau yang mendukakan, kau dan aku dan semua manusia memiliki hati yang luas di mana semua lara dan luka dapat ditanggung dan diberi makna. Inilah satu dari dua hal yang membuat aku berani berharap sekali lagi, dan sekali lagi, ketika patah hati. Sebab aku tak melihat ada jalan lain yang lebih baik dari ‘berharap sekali lagi’, meski tak selalu harus pada orang atau kisah yang sama.
Harapan tak boleh mati — harapan butuh makna. Aku percaya, bahwa kau dan aku adalah satu-satunya manusia yang paling bisa diandalkan untuk memberi kepada diri kita makna — dan dari situ akan datang kekuatan dan keberanian. Di dalam patah dan lara, sebuah kekecewaan yang gelap dan tak terkendali, manusia hanya punya dua pilihan: menolak atau menerima kenyataan. Bagiku, sekalipun pahit dan panas, terimalah apa yang nyata. Sebab di dalam penerimaan itu, kau dan aku belajar mengumpulkan segenap kekuatan untuk percaya bahwa kekayaan dari kebaikan hidup akan mengajari jari-jari kita untuk menyulam makna. Selama kau dan aku percaya pada adanya kebaikan, bahkan dalam masa-masa paling kelam, kebaikan yang kau dan aku percayai itu akan menolong kita untuk bergerak maju dan — dalam cara-cara yang semula tak terbayangkan — akan mengubah hidup kita.
Kehidupan mengisi dirinya dengan tak terbilang banyaknya ketidakpastian. Pengalaman demi pengalaman membuktikannya. Tak ada yang pasti. Di dalam semua yang tak pasti, manusia mengisi dirinya dengan dua hal: cinta dan takut. Manusia yang mengisi hatinya dengan ketakutan akan sedapat mungkin mengambil jarak dari kehidupan. Hatinya menjadi sempit dan ia terpenjara di dalamnya. “Jangan sampai patah hati (lagi),” begitu pikirmu. Namun, manusia yang mengisi hatinya dengan cinta akan berani menceburkan diri ke dalam hidup yang maha samudra. Hatinya akan cukup lapang untuk menanggung semua ketidakpastian termasuk, “Jangan-jangan patah lagi nanti.” Meski memang tidak ada jaminan bahwa kau dan aku akan mengalami hidup yang sesuai harapan, tetapi “Di dalam semua ketidakpastiani ini, adakah yang lebih baik dari memilih cinta atau jatuh cinta (lagi)?”
Mencintai (lagi), lalu patah (lagi), dan tetap percaya kepada cinta, bagiku, adalah pengalaman sejati tentang hidup — dan sejatinya kehidupan manusia memang demikian.
____